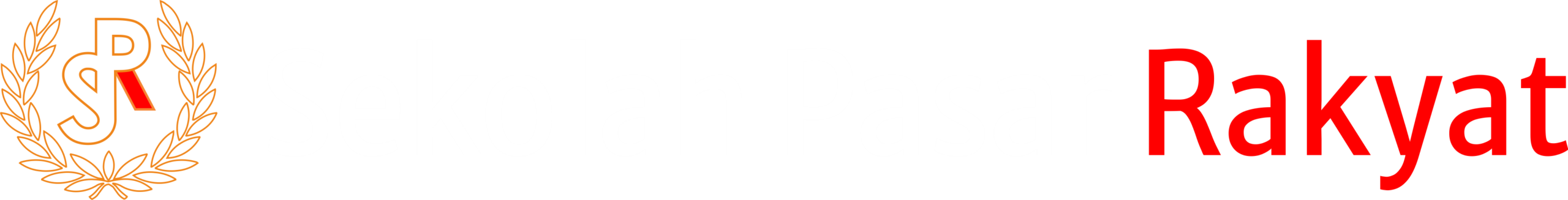Khittah Pasar Rakyat
Pasar adalah tempat “syi’ar”, bersuara, atau berkumandang. Lazimnya tentu diutamakan apa isi pesan atau suaranya, meski tidak boleh pula mengabaikan siapa dan bagaimana menyampaikannya. Begitulah pasar rakyat pun diibaratkan. Seperti apa isi pasarnya adalah sepenting siapa pelaku di dalamnya dan bagaimana bangunannya diperlihatkan. Pasar rakyat mengandung syi’ar kreativitas dan kemandirian rakyat tatkala ia berisi aneka produk olahan yang tidak pernah putus diperbarukan. Ia menjadi tempat menjual beras dan sayur organik, sabun herbal dari minyak kelapa, pasta gigi dari ekstrak sirih, sampo dari merang, beras organik, es krim ketela, aneka coklat olahan, dan berbagai komoditi lain yang mampu dihasilkan rakyat secara mandiri sesuai potensi alam sekitar.
Pasar akan menyuarakan kebersamaan ekonomi ketika barang-barang tersebut dihasilkan oleh serikat rakyat, kooperasi, dan berbagai usaha kolektif yang tumbuh berkembang di desa sekitar. Dan sejatinya dua pesan itulah khitah pasar rakyat, sebagai gerbong pemaju dan pembaruan desa dan masyarakat sekitar. Demikian khittah pasar rakyat. Ia bukanlah pen-syiar bisnis perusahaan transnasional yang telah merenggut pengetahuan tradisonal rakyat yang dulu lama berakar. Namun menjadi ironis ketika saat ini urusan di kamar mandi dan dapur pun kita pasrahkan pada pemodal yang berada nun jauh di Den Hag, New York, ataupun Paris. Dan sekali lagi itu bukan hanya terjadi di mal, hypermarket, minimarket, tetapi juga di pasar rakyat
Persaingan dengan ritel modern kian tidak seimbang karena produk yang dijual relatif serupa. Akibatnya, sebagian omset pasar rakyat turun drastis 30-60%, pun tak sedikit yang terpaksa harus ditutup. Situasi yang kiranya paradoksal, ketika di sisi pasokan survey BPS (2006) menemukan bahwa masalah utama pelaku UMKM di DIY adalah sulitnya pemasaran (34%). Pun masih banyak UMKM utamanya yang di daerah pedesaan terjerat tengkulak dan oligopsonis penguasa pasar.
Hukum Rimba di Pasar
Sudah jamak kiranya banyak regulasi yang sekadar meninimalisir dampak dari ketelanjuran. Ia kemudian hanya menjadi stempel legalisasi dari keadaan yang sudah terjadi. Pun seperti itu regulasi tentang pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern diadakan. Seperti apa struktur perdagangan ideal, serta arah dan model pemberdayaan pasar rakyat tidak pernah jelas dan tegas diutarakan.
Perpres 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern pun jauh dari fungsi“law as a social engineering”. Tentu bukan kontruksi sosial di mana perdagangan didominasi segelintir elit korporasi seperti saat sekarang yang kita citakan. Dalam konteks ini, visi Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) jelas bahwa perdagangan hendaknya dipimpin dan dikontrol oleh jutaan rakyat pedagang. Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dengan demikian adalah mengatur bagaimana pelaksanaan visi tersebut melalui UU, PP, dan Peraturan Daerah. Bahwa yang terjadi saat ini sebaliknya kiranya menyiratkan regulasi kita masih mengadopsi “hukum rimba” dengan visinya “survival for the fittest”. Siapa yang kuat dialah yang bertahan dan menang, kemudian siapa yang menang boleh menguasai semuanya (the winner take all). Lalu bagaimana regulasi bisa berarti tanpa visi?
Kini bahkan tanggung jawab pemerintah tersebut kian direduksi sekadar menjaga supaya pedagang rakyat tetap bertahan, bukan lagi sebagai pemain utama seperti yang diamanahkan. Alih-alih memposisikan pasar rakyat sebagai agen kemandirian rakyat, pun alat perjuangan untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar.
Makin Menjadi “Bangsa Pasar”
Pada akhirnya bangsa kita tetap tertinggal sungguhpun telah ratusan fakultas teknik, MIPA, ekonomi dan ahli-ahlinya yang kita miliki. Ekonomi kita terus menjadi pasar setia produk-produk olahan dari industri luar negeri. Kita biarkan masyarakat kita–bahkan sampai yang di pelosok-pelosok desa—menjadi pasar bagi pabrik-pabrik perusahaan luar negeri.
Penetrasi ritel modern yang kian massif hingga di daerah perdesaan telah mengarahkan tatanan pasar yang kian didominasi elit pemodal besar. Dan bahkan telah ratusan (ribuan?) fakultas hukum dan ahli-ahlinya lama yang kita miliki, namun Undang-Undang Ekonomi kita hingga saat ini pun masih selalu dibuat, dipesan, dan diatur-atur oleh pihak luar negeri. Regulasi kita masih menjadi pasar yang memikat bagi pemesan-pemesan bermodal dan berkuasa besar dari luar negeri tersebut.
Pada saat yang sama, perusahaan negara (BUMN) hanya sanggup kita juali. Koperasi dan perusahaan rakyat masih kita perlakukan bak anak tiri. Pasar modal 67%-nya didominasi perusahaan luar negeri. Pun, jurus andalan ekonom kita selalu adalah “gali lobang tutup lobang” melalui pembuatan utang dalam dan luar negeri. Kita pun terus menjadi pasar bagi kreditur pemburu rente dari luar negeri.
Demikian, kita makin hanya menjadi “bangsa pasar”, sungguhpun kita masih memiliki 52 juta UMKM dan 13.500 pasar rakyat. Kita lebih banyak membeli, ketimbang membuat dan mengkreasi. Padahal, pasar tanpa kecukupan industrialis dan wirausahawan desa hanya akan memperbesar usaha dan memperbanyak pekerjaan bagi bangsa luar. Dan akhirnya pun nasib terus saja memaksa saudara kita berebut zakat di antrian, terpuruk di kota-kota besar, dan teraniaya di negeri orang.
Jalan Menjadi Bangsa Besar
Sekarang semestinyalah kita sadar bahwa yang perlu direvitalisasi, ditata ulang bukan sekadar bangunan fisik pasar. Tetapi ia adalah perasaan sebagai bangsa besar, yang mampu mengkreasi daripada sekadar menikmati, dengan terus berusaha untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hal ini tentu melampaui pemikiran undang-undang. Karena ia adalah ruh (jiwa) yang membangunkan impian seluruh eleman anak bangsa, untuk segera berhenti sekadar menjadi kuli atau pasar di negeri sendiri.
Seandainya ritel dan pusat perbelanjaan modern lebih merupakan kepanjangan tangan segelintir perusahaan transnasional, maka pasar rakyat tidak boleh mengambil posisi yang serupa, Semestinyalah pasar rakyat menjadi agen pemandirian dan pemajuan 13 juta pedagang kecil dan ekonomi-nya rakyat, desa, dan bangsa Indonesia. Pasar rakyat jika begitu adalah pilihan bagi siapapun yang menginginkan kita kembali menjadi bangsa besar. Sekali lagi, itulah khittah pasar rakyat.
Oleh karena itu, seharusnyalah kita dirikan kembali pasar kita, dengan menghidupkan kembali pengetahuan rakyat masyarakat desa, dengan segenap kelimpahan karunia alam dan teknologi yang ada. Bukan dengan mengharap-harap bantuan dan perhatian pemodal besar, tidak pula sekadar dengan begitu banyak peraturan. Pasar tradisional ataupun pasar rakyat akan jaya jika kita semua mau berubah dengan tidak lagi sekadar menjadi “bangsa pasar”.
Awan Santosa, SE, MSc.
Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dan Dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Sumber: Sekolah Pasar Rakyat, 2013